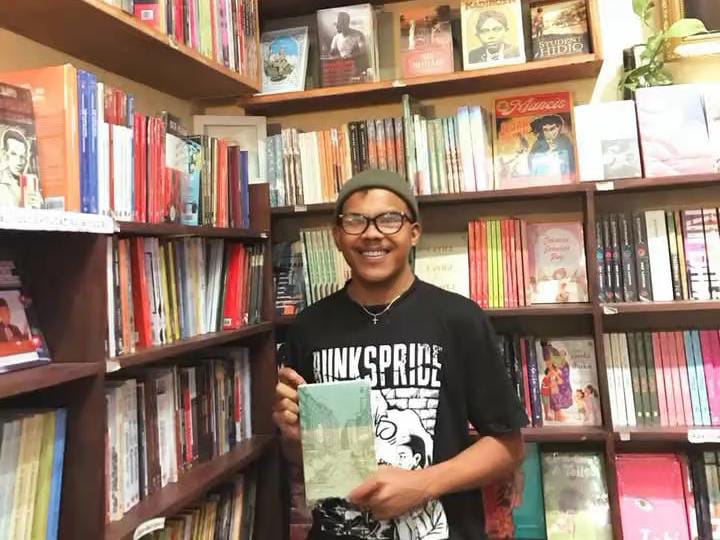ibnchannel.id – Di tengah sorotan publik terhadap pendidikan formal yang semakin mahal dan eksklusif, muncul kembali perhatian pada sesuatu yang sering luput dari radar kebijakan: Sekolah Rakyat. Di banyak daerah, istilah ini bukan sekadar nama lembaga, tapi simbol perjuangan — tempat belajar yang tumbuh dari semangat masyarakat, bukan dari struktur birokrasi.
Ia lahir dari kebutuhan, bukan peraturan; dari kepedulian, bukan dana negara. Namun di balik idealisme itu, tersembunyi kisah panjang tentang ketimpangan, keteguhan, dan harapan yang belum sepenuhnya mendapat tempat dalam sistem pendidikan nasional.
Warisan Lama yang Belum Usang
Sekolah Rakyat pertama kali dikenal sebagai warisan masa awal kemerdekaan. Dulu, ia menjadi wujud nyata cita-cita pendidikan untuk semua. Namun dalam perjalanan waktu, istilah itu menghilang dari dokumen resmi. Sistem pendidikan formal berkembang dengan jenjang yang jelas — SD, SMP, SMA — sementara semangat “rakyat” justru terkubur di bawah tumpukan regulasi dan angka akreditasi.
Ironisnya, di banyak pelosok negeri, Sekolah Rakyat masih tetap hidup, meski dengan wajah berbeda. Ada yang berbentuk sekolah alternatif, sekolah komunitas, hingga pusat belajar berbasis kearifan lokal. Mereka menampung anak-anak yang tidak mampu masuk sekolah formal, anak yang terpinggirkan karena jarak, kemiskinan, atau kebijakan yang tidak ramah terhadap kondisi mereka.
Di Papua, ada Sekolah Rakyat yang berdiri di tengah kampung terpencil tanpa listrik. Di Lombok, sekolah rakyat berdiri di gubuk bambu, dijalankan oleh relawan yang hanya dibayar dengan hasil panen. Di Jakarta sekalipun, ada sekolah rakyat yang menampung anak jalanan dan pekerja anak, mengajarkan baca tulis serta keterampilan hidup.
Semuanya berjalan dalam senyap, tanpa perhatian negara, tapi menyala oleh semangat rakyat yang menolak menyerah pada nasib.
Potret Ketimpangan dalam Akses dan Struktur
Ketika pemerintah gembar-gembor soal “pemerataan pendidikan”, realitas di lapangan justru menunjukkan kesenjangan yang melebar. Sekolah negeri berkualitas masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Sementara di pedesaan, banyak anak bahkan tidak punya sekolah dasar yang layak.
Di sinilah Sekolah Rakyat hadir sebagai jembatan, tapi sayangnya tanpa fondasi yang kokoh.
Sebagian sekolah rakyat tidak memiliki izin resmi, karena terkendala aturan administratif yang sulit dipenuhi. Misalnya, syarat memiliki guru bersertifikat, jumlah murid minimal, hingga fasilitas bangunan permanen. Padahal, syarat-syarat itu hampir mustahil dipenuhi di wilayah yang bahkan tidak punya jalan aspal.
Akibatnya, sekolah rakyat sering berada di zona abu-abu: tidak diakui negara, tapi diandalkan masyarakat.
Anak-anak yang belajar di sana sering kesulitan ketika ingin melanjutkan ke sekolah formal, karena ijazah mereka tidak diakui. Sebuah ironi dalam negara yang mengaku menjamin hak pendidikan bagi semua.
Bukan Sekadar Tempat Belajar, Tapi Gerakan Sosial
Sekolah Rakyat sejatinya lebih dari sekadar ruang kelas. Ia adalah gerakan sosial yang berakar dari partisipasi warga. Di banyak tempat, pendirinya bukan guru formal, melainkan petani, aktivis, atau tokoh masyarakat yang peduli. Mereka percaya bahwa pendidikan bukan milik elite, tetapi hak setiap manusia.
Model pendidikan yang mereka jalankan biasanya jauh dari kurikulum kaku. Anak-anak diajak belajar dari kehidupan sehari-hari: mengenal lingkungan, bertani, berdialog, atau membuat kerajinan. Fokusnya bukan nilai ujian, tapi kemampuan berpikir kritis dan empati sosial.
Itulah mengapa sekolah rakyat sering dianggap “subversif” oleh sistem — karena mereka tidak tunduk sepenuhnya pada aturan, tapi berani merumuskan pendidikan dengan caranya sendiri.
Namun dalam pandangan yang lebih jernih, justru di situlah letak kekuatannya. Sekolah rakyat menawarkan bentuk pendidikan yang manusiawi: dekat dengan realitas, sederhana tapi bermakna, dan menumbuhkan kesadaran akan martabat diri.
Dalam konteks bangsa yang masih terjebak pada logika kompetisi akademik, sekolah rakyat mengajarkan nilai kebersamaan — bahwa tujuan belajar bukan untuk naik kelas, melainkan untuk memahami hidup.
Kebijakan yang Tak Pernah Akomodatif
Masalah terbesar Sekolah Rakyat bukan pada idealismenya, melainkan pada cara negara memperlakukannya.
Pemerintah sering memandang sekolah semacam ini sebagai “pelengkap”, bukan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Akibatnya, mereka tidak masuk dalam skema bantuan operasional sekolah, tidak mendapat pendampingan guru, dan sering dianggap tidak memenuhi standar.
Padahal, jika mau jujur, keberadaan sekolah rakyat justru menambal kekosongan yang belum bisa diisi pemerintah. Mereka hadir di tempat negara absen: di gunung, pesisir, dan perkampungan miskin perkotaan.
Alih-alih diberi ruang, banyak dari mereka justru ditekan oleh birokrasi. Ada sekolah yang dibubarkan karena dianggap tidak memiliki izin. Ada pula yang kesulitan menerima bantuan karena tidak punya rekening resmi.
Negara terlalu sibuk menata regulasi, tapi lupa bahwa pendidikan sejatinya adalah tentang manusia — bukan sekadar angka dan akreditasi.***
Artikel ini ditulis berdasarkan pendapat kontributor Laurensius Bagus, mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta dan aktivis sosial.